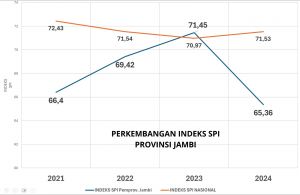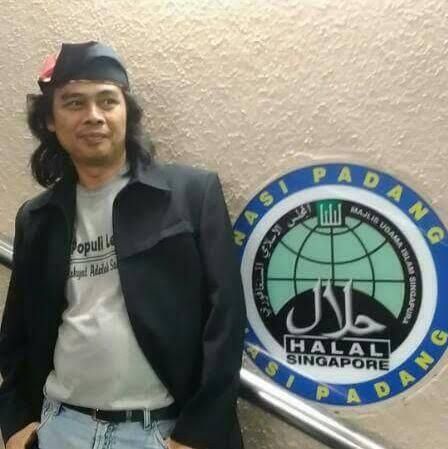
Oleh: Musri Nauli*
Indonesia, dengan tekad bulat, telah menancapkan komitmennya dalam upaya global mengatasi perubahan iklim.
Setelah meratifikasi Perjanjian Paris melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016, pemerintah secara serius menempatkan isu ini dalam agenda pembangunan nasional, tercermin dalam visi Nawacita 2019-2024 dan Astacita 2024-2029. Targetnya pun ambisius: mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29% dengan usaha sendiri, dan mencapai 43% dengan dukungan internasional pada tahun 2030, yang dikenal sebagai Indonesia National Determined Contribution (NDC 2030).
Sektor kehutanan, sebagai penyumbang emisi terbesar kedua di Indonesia, memegang peranan kunci dalam pencapaian target ini, dengan program ambisius "Follu Net Sink" yang menargetkan pengurangan emisi GRK sebesar 140 Juta CO2e pada tahun 2030.
Provinsi Jambi tak ketinggalan dalam barisan terdepan.
Berbagai regulasi daerah telah disusun untuk mendukung pencapaian target Folu Net Sink 2030, termasuk Peraturan Daerah (Perda) terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Lebih istimewa lagi, Jambi memiliki Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pertumbuhan Ekonomi Hijau, sebuah peta jalan komprehensif yang menguraikan strategi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui penatagunaan lahan, pemulihan ekosistem, peningkatan produktivitas, pengembangan kapasitas SDM, serta konektivitas dan rantai nilai yang berkelanjutan.
Salah satu implementasi nyata dari Peta Jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Jambi adalah optimalisasi program Bio-Carbon Fund – Initiative for Sustainable Forest Landscape (BioCF-ISFL) 2021-2025. Program ini diharapkan mampu menurunkan emisi GRK sebesar 19 Juta Ton CO2e antara tahun 2020-2025, melebihi target penurunan emisi GRK Provinsi Jambi sebesar 14 Juta Ton CO2e yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026. Lebih dari sekadar angka, BioCF-ISFL juga diharapkan mendorong sinergi berbagai pihak dan mempercepat pembangunan rendah emisi di Jambi. Kontribusi Jambi ini, pada akhirnya, akan sepenuhnya dialokasikan untuk mendukung target nasional Folu Net Sink dan NDC 2030 Indonesia.
Keberhasilan target Folu Net Sink 2030 di Jambi sangat bergantung pada kolaborasi multi-pihak. Pemerintah, sektor swasta, dan mitra lainnya seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Perguruan Tinggi, memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi bertindak sebagai koordinator utama untuk seluruh kegiatan BioCF dan Folu Net Sink di Jambi.
Sementara itu, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi menjadi "leading sector" yang bertanggung jawab langsung atas program ini, mencakup pemulihan hutan dan gambut, penguatan perhutanan sosial, hingga penghitungan capaian karbon. Berbagai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) juga turut terlibat aktif, menunjukkan upaya kolektif yang terkoordinasi.
Penting untuk dicatat bahwa Pemerintah Provinsi Jambi telah menyelaraskan rencana penurunan emisi GRK ini dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, memastikan bahwa target Folu Net Sink sejalan dengan target "Green Growth Plan" (GGP) provinsi yang mencakup pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, inklusif, ketahanan sosial-ekonomi, ekosistem sehat, dan penurunan efek gas rumah kaca.
Namun, di balik komitmen yang kuat dan kerangka kebijakan yang matang, Provinsi Jambi masih menghadapi sejumlah tantangan. Rotasi pejabat daerah yang tinggi menjadi kendala dalam internalisasi kebijakan pertumbuhan ekonomi hijau dan program-program pendukungnya seperti BioCF-ISFL dan Green Climate Fund (GCF) Output 2. Hal ini menyebabkan sosialisasi program menjadi berulang dari waktu ke waktu.
Selain itu, pemerintah kabupaten cenderung menyerahkan penanganan dan pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) kepada pemerintah pusat, dengan alokasi anggaran yang minim untuk perlindungan ekosistem lahan gambut.
Belum adanya regulasi spesifik yang mengatur penggunaan dana desa untuk perlindungan lahan gambut juga menjadi kekhawatiran bagi pemerintah desa dalam mengalokasikan anggaran. Tantangan-tantangan ini memerlukan perhatian serius dan solusi inovatif untuk memastikan keberlanjutan program dan pencapaian target.
Upaya Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim melalui pendekatan ekonomi diperkuat oleh kerangka hukum yang progresif dan terstruktur. Beberapa peraturan kunci menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK):
* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Ratifikasi Kesepakatan Paris: Ini adalah fondasi hukum yang mengesahkan komitmen Indonesia terhadap Perjanjian Paris, yang bertujuan membatasi kenaikan suhu global di bawah 2°C, bahkan berupaya mencapai 1,5°C dari tingkat pra-industrialisasi.
UU ini menegaskan kewajiban setiap negara pihak untuk melaksanakan dan mengomunikasikan upaya ambisius terkait NDC, adaptasi, serta dukungan pendanaan, teknologi, dan pengembangan kapasitas. NDC Indonesia mencakup mitigasi dan adaptasi, dengan target pengurangan emisi yang jelas, dicapai melalui sektor-sektor seperti kehutanan, energi, limbah, industri, dan pertanian.
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup: Meskipun tidak secara langsung menyebut "pembagian manfaat karbon", PP ini mengatur instrumen ekonomi lingkungan hidup yang dapat mendorong pelestarian lingkungan. Ia memperkenalkan gagasan bahwa masalah lingkungan dapat diatasi melalui mekanisme pasar dan insentif ekonomi, sebuah pergeseran paradigma penting yang mengakui bahwa perilaku ekonomi dapat dibentuk untuk tujuan lingkungan. Konsep "Perdagangan Izin Pembuangan Limbah dan/atau Emisi" dalam PP ini memiliki relevansi kuat dengan konsep perdagangan emisi karbon.
Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon: Perpres ini menjadi tonggak utama dalam kebijakan iklim Indonesia, secara eksplisit dan komprehensif mengatur NEK untuk mencapai target NDC. Ini adalah respons langsung terhadap ratifikasi Perjanjian Paris dan komitmen NDC Indonesia. Perpres ini mengukuhkan karbon sebagai indikator universal kinerja pengendalian perubahan iklim yang memiliki nilai ekonomi penting. Tiga mekanisme utama NEK diidentifikasi: Perdagangan Karbon (mencakup Perdagangan Emisi dan Offset Emisi GRK), Pembayaran Berbasis Kinerja, dan Pungutan Atas Karbon. Perpres ini juga sangat menekankan transparansi melalui Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi (MRV) serta Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI), dengan sanksi administratif bagi pelanggaran.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon: Sebagai peraturan pelaksana langsung dari Perpres 98/2021, Permen LHK ini merinci tata laksana operasional penerapan NEK secara lintas sektor. Ia memberikan detail lebih lanjut tentang pelaksanaan Perdagangan Karbon, Pembayaran Berbasis Kinerja, dan Pungutan atas Karbon. Peraturan ini juga mengukuhkan SRN PPI sebagai sistem sentral untuk pencatatan dan pelaporan seluruh kegiatan NEK, termasuk penerbitan Sertifikat Pengurangan Emisi GRK (SPE-GRK).
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan: Peraturan ini secara spesifik mengatur perdagangan karbon di sektor kehutanan, salah satu mekanisme NEK.
Permen ini berfungsi sebagai penjabaran lebih lanjut dari Permen LHK 21/2022, khusus untuk sektor kehutanan, dan menetapkan dasar bagi perdagangan karbon untuk mengendalikan Emisi GRK dan mencapai target NDC sektor kehutanan.
Secara keseluruhan, hierarki peraturan ini menunjukkan komitmen politik yang kuat dari pemerintah pusat dalam mengatur NEK, dengan Perpres 98/2021 sebagai regulasi tertinggi dalam konteks ini, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh Permen LHK untuk implementasi operasional di berbagai sektor, khususnya
Dalam konteks regulasi biokarbon di Indonesia, mekanisme pembagian manfaat diatur untuk memastikan pencapaian target pengurangan emisi GRK dan memberikan insentif bagi pihak-pihak yang berkontribusi. Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021, mencakup pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui NEK untuk mencapai target NDC. Pelaksana NEK dapat melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.
Penting untuk dicatat bahwa pembayaran berbasis kinerja (result-based payments) adalah salah satu mekanisme yang digunakan dalam NEK. Tujuan NEK sendiri adalah menjadi insentif untuk pencapaian NDC, mendukung upaya pengendalian kebakaran hutan, pencegahan deforestasi dan degradasi hutan, serta transisi teknologi untuk energi baru terbarukan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 70 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan REDD+, penerima manfaat dapat mencakup kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.
Aspek pembagian manfaat dilakukan dengan mengedepankan kewenangan, kinerja pengurangan emisi GRK, serta upaya atau aksi untuk tidak mengeluarkan emisi GRK. Contoh implementasi nyata terlihat pada peran Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) yang memfasilitasi perdagangan karbon dan menerima pembiayaan dari program REDD+ di Indonesia, yang dananya akan didistribusikan kepada penerima manfaat. Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) juga menekankan pentingnya memastikan hak seluruh pemangku kepentingan, terutama masyarakat, atas manfaat Program FCPF Carbon Fund.
Di Provinsi Jambi, Pemerintah Provinsi melalui Sub Nasional Manajemen Unit (SNPMU) secara aktif menyosialisasikan pola penetapan dan pengukuran emisi, penetapan dan skema pembagian manfaat, serta tata cara penyaluran manfaat.
Bahkan, manfaat dari karbon dari menjaga hutan dan mencegah emisi di Jambi telah didistribusikan kepada masyarakat, melalui berbagai bentuk seperti sunatan massal, distribusi sembako, pembangunan sarana dan prasarana desa, dan dukungan untuk pengelola hutan desa. Perlindungan hak masyarakat, termasuk masyarakat adat dan lokal, dalam pembagian manfaat juga menjadi perhatian utama.
Secara ringkas, Indonesia, melalui kerangka hukum yang kuat dan komitmen daerah seperti Provinsi Jambi, sedang merajut masa depan hijau yang lebih berkelanjutan.
Meskipun tantangan masih membayangi, semangat kolaborasi dan inovasi diharapkan mampu mendorong pencapaian target-target ambisius dalam pengendalian perubahan iklim, demi bumi yang lebih lestari untuk generasi mendatang.
Advokat. Tinggal di Jambi*

Bupati Anwar Sadat Safari Subuh di Masjid Al Namira RT 10 Parit Gompong

Wabup Katamso Tegaskan Komitmen Pemerintah Daerah Perkuat Swasembada Pangan

Aulia Salsabila Raih Prediket Cumlaude, Persembahan di Wisuda Untuk Orangtua - Almamater



Serangan Israel ke Iran: Pelanggaran Terang-Terangan terhadap Hukum Internasional


Membanggakan! 9 Mahasiswa Nilai Tertinggi-IPK 4.00 di Wisuda Ke-III UBR Jambi, Berikut Nama-namanya